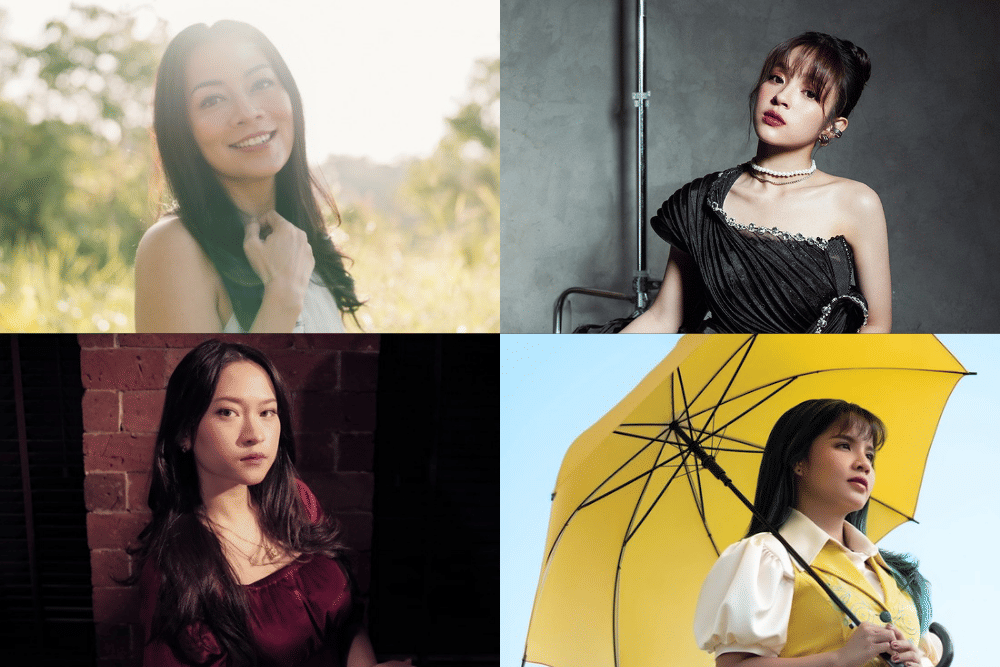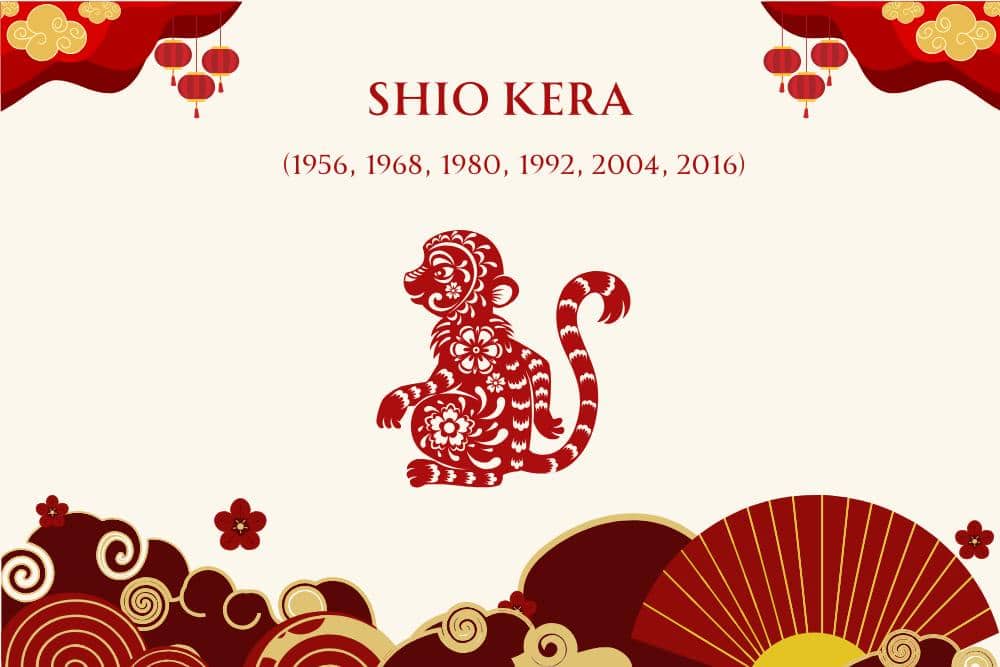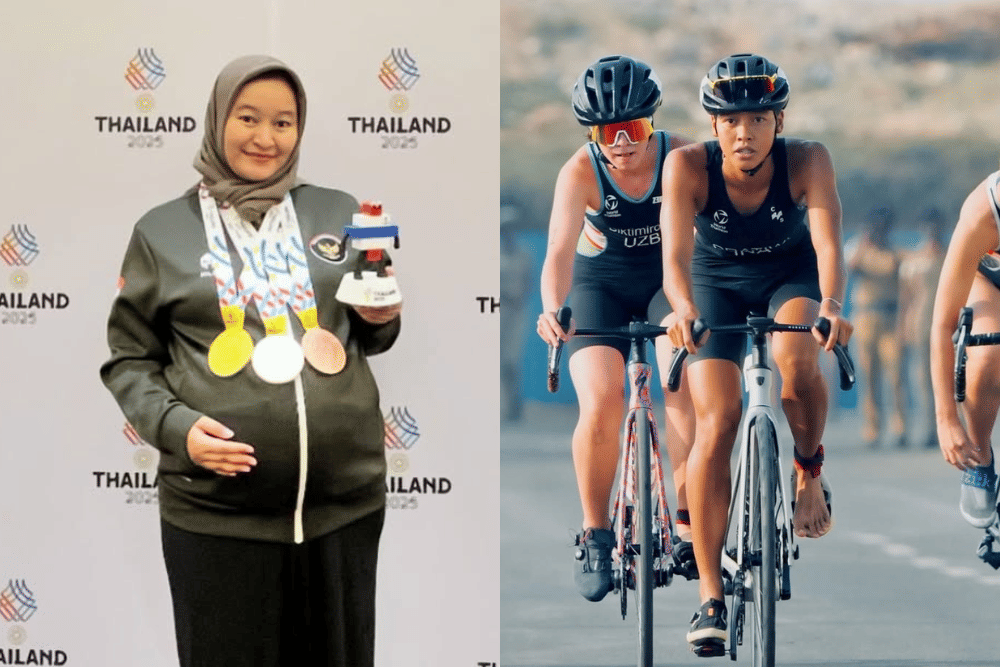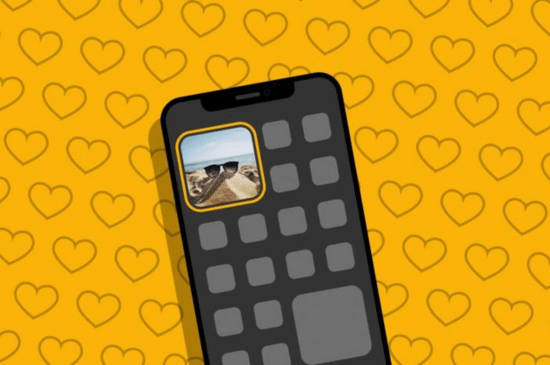'Devi', Perjuangan Perempuan Melawan Kekerasan Seksual

Film Devi karya sutradara Subina Shrestha menyoroti kisah perjuangan perempuan Nepal yang mencoba melawan kekerasan seksual di tengah budaya patriarki yang menindas. Kisah bagaimana sosok Devi mencari keadilan untuk kasus kekerasan seksual yang dialaminya, benar-benar menyentuh hati dan membuka mata penonton terkait masih begitu sulitnya perempuan mendapat keadilan. Bukan hanya di Nepal, tapi juga di berbagai belahan dunia.
POPBELA berkesempatan untuk menonton langsung dan mengikuti diskusi bersama bersama aktivis Kalis Mardiasih dan Subina Shrestha sebagai rangkaian dari acara Alternativa Film Festival 2024 di Yogyakarta. Dalam diskusi yang berlangsung pada 27 November 2024 dan berdurasi selama satu jam tersebut, Khalis dan Subina mengungkapkan pelajaran mendalam tentang keteguhan, persatuan, dan pentingnya dukungan untuk melawan ketidakadilan.
Berikut adalah rangkuman dari diskusi tersebut.
Perjuangan bertahun-tahun untuk hak yang masih terbengkalai

Subina menyatakan, Devi adalah simbol kekuatan perempuan yang tak pernah menyerah, meski menghadapi banyak rintangan. Sejak belasan tahun lalu, ia memperjuangkan hak korban kekerasan seksual di Nepal, sebuah negara dengan budaya yang sering kali meminggirkan isu perempuan. Meski perjalanan panjangnya belum membuahkan hasil nyata, Devi tetap berdiri teguh untuk suara-suara yang selama ini dibungkam.
Kisah ini mencerminkan bagaimana keadilan sering kali menjadi sesuatu yang jauh dari jangkauan perempuan korban kekerasan seksual. Tidak hanya di Nepal, tetapi di banyak negara, termasuk Indonesia, perempuan masih harus bertarung melawan sistem yang enggan mengakui penderitaan mereka. Perjuangan Devi adalah pengingat bahwa keteguhan adalah senjata utama untuk melawan ketidakadilan, meskipun hasilnya belum terlihat.
Persatuan perempuan: dari sebelas menjadi seribu

Bukan cuma soal perjuangan, kisah Devi mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Perjuangannya awalnya hanya melibatkan sebelas orang perempuan yang memiliki keberanian untuk bersuara. Namun, keberanian itu menyebar seperti api yang membakar ketidakadilan, hingga akhirnya menggerakkan ribuan orang untuk bersatu.
Kalis Mardiasih menyoroti bahwa solidaritas perempuan adalah kunci untuk melawan budaya kekerasan seksual. Ketika perempuan bersatu, mereka menjadi kekuatan yang sulit diabaikan. Bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai kekuatan nyata untuk menuntut keadilan yang layak mereka dapatkan.
Kenapa kekerasan seksual berbeda dengan kejahatan lainnya?

Menurut Kalis Mardiasih, kekerasan seksual adalah kejahatan yang paling menghancurkan martabat manusia. Jika kejahatan biasa hanya merenggut barang fisik, kekerasan seksual mencuri harga diri, rasa aman, dan identitas seseorang. Ini menjadi luka batin yang sulit disembuhkan, sering kali membuat korban merasa malu dan memilih untuk diam.
Kalis menekankan bahwa kita harus membangun ruang aman bagi para korban untuk berbicara. Kekerasan seksual bukanlah hal yang bisa dilupakan atau dibiarkan begitu saja. Sebaliknya, hal ini harus menjadi perhatian utama, karena menyangkut esensi kemanusiaan yang paling mendasar.
Indonesia dan Nepal cermin yang sama dalam sejarah kelam kasus kekerasan seksual
Seperti yang tergambar dalam Devi, Indonesia juga memiliki sejarah kelam terkait kekerasan seksual, terutama saat kerusuhan 1998. Ribuan perempuan menjadi korban, namun hingga kini, pemerintah belum menunjukkan langkah nyata untuk mengakui atau meminta maaf atas kejadian tersebut. Kasus ini menjadi bukti bahwa kekerasan seksual sering kali diabaikan oleh pemerintah, baik di Nepal maupun Indonesia.
Diskusi dengan Kalis dan Subina menyoroti pentingnya mengingat dan terus memperjuangkan keadilan bagi para korban. Jika negara terus tutup mata, maka perjuangan perempuan untuk melawan kekerasan seksual akan menjadi lebih berat. Perlu ada dorongan kolektif dari masyarakat untuk memastikan isu ini tidak lagi disembunyikan.
Pemerkosaan sebagai bentuk kekuasaan, bukan hasrat
Subina menegaskan bahwa pemerkosaan, terutama dalam konteks perang, adalah bentuk penindasan paling kejam terhadap perempuan. Hal ini bukan tentang hasrat seksual, melainkan tentang kekuasaan dan kontrol. Sayangnya, hukum sering kali gagal memahami ini, dengan definisi pemerkosaan yang terlalu sempit dan tidak memadai untuk melindungi korban.
Di Indonesia, UU TPKS adalah langkah maju, tetapi implementasinya masih jauh dari sempurna. Banyak korban yang baru berani melapor setelah bertahun-tahun, namun sering kali bukti sudah hilang, membuat laporan mereka dianggap tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih memihak pelaku, bukan korban. Perjuangan feminis untuk mereformasi sistem hukum terus berjalan, tetapi membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk laki-laki, untuk menciptakan perubahan nyata.
Film Devi dan diskusi ini mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan kekerasan seksual adalah perjuangan yang membutuhkan ketekunan, keberanian, dan solidaritas. Perempuan, meski terluka, tetap berdiri untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih adil. Mari terus bicara, bergerak, dan melawan bersama agar keadilan untuk perempuan bisa diwujudkan.